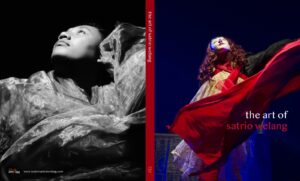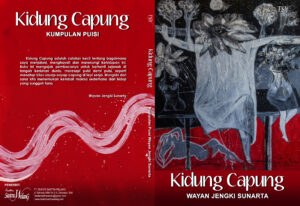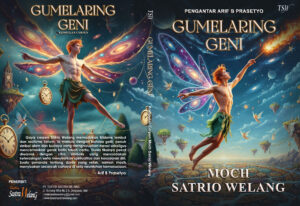Ilustrasi: Internet
KOMUNITAS-KOMUNITAS sastra yang tumbuh di Indonesia, termasuk di Bali, patut diakui telah ikut mewarnai kehidupan sastra. Fenomena ini pernah ditulis sastrawan Sutardji Calzoum Bachri (SCB) dalam esainya berjudul “Sastra Komunitas” di harian Kompas. Ia menyoroti gejala yang pada mulanya tampak positif, banyaknya komunitas sastra yang muncul di berbagai daerah, menjadi wadah berkumpul para pengarang, seniman, dan pecinta sastra.
SCB menggambarkan betapa komunitas-komunitas ini menjalankan beragam aktivitas, mulai dari diskusi, pembacaan puisi, pementasan teater, penerbitan buku, hingga obrolan di warung kopi. Ia melihat bahwa komunitas dapat memperkaya karya seorang pengarang, dan sebaliknya, karya pengarang bisa memberi arah bagi komunitas. Dengan kata lain, komunitas menjadi simpul penting dalam peta sastra Indonesia kontemporer.
Tetapi, seperti biasa, SCB tidak berhenti pada pujian. Ia juga melontarkan kritik tajam. Menurutnya, banyak komunitas sastra di Indonesia cenderung “asyik sendiri.” Komunitas-komunitas itu sibuk dengan selera internalnya, lebih senang merayakan dirinya sendiri, dan kurang membuka diri pada masyarakat luas.
Kritik sastra yang muncul pun sering kali tidak objektif. Kritikus baru tampil jika diundang komunitas, atau menulis di media massa yang berafiliasi dengan komunitas tertentu. Akibatnya, kritik berubah menjadi basa-basi, sekadar hiburan untuk tuan rumah, bukan pisau tajam yang menyingkap lapisan terdalam karya sastra.
Bagi SCB, keadaan ini berbahaya. Ia menyebut bahwa kesusastraan Indonesia kini cenderung menjadi “kesusastraan komunitas”, kumpulan produk yang lahir dari komunitas-komunitas, dengan bias dan selera yang berbeda-beda. Karena itu ia mengusulkan perlunya studi mendalam dan obyektif tentang komunitas sastra, lebih konkret ketimbang cultural studies yang baginya sering kali kurang relevan.
Pertanyaannya, apakah benar komunitas sastra hanya “asyik sendiri”? Ataukah ada wajah lain yang lebih kompleks?
Sebelum menjawab, kita perlu menempatkan komunitas sastra sebagai gejala sosial. Sejarah sastra Indonesia menunjukkan bahwa komunitas selalu hadir dalam berbagai bentuk. Pada masa 1960-an, ada Lekra dan Manikebu yang membawa visi politik dan ideologi besar. Pada dekade 1980-an, muncul komunitas-komunitas kampus, sanggar, atau kelompok diskusi yang memunculkan nama-nama baru. Di era 2000-an, komunitas sastra menyebar luas, bahkan sampai ke kota kecil, berkat dorongan media sosial, festival, dan tradisi literasi yang semakin cair.
Komunitas tidak pernah netral. Ia selalu punya warna, dipengaruhi tokoh sentral, visi estetik, bahkan ideologi tertentu. SCB benar ketika menyebut ada komunitas yang religius, sekuler, elitis, santai, atau bahkan anti-intelektual. Komunitas adalah cermin kecil dari kehidupan sosial kita yang plural.
Namun, di sinilah letak dilema. Di satu sisi, komunitas adalah rumah yang menghangatkan, tempat sastrawan muda menemukan sahabat sepenanggungan. Di sisi lain, komunitas bisa berubah menjadi tembok, membatasi pandangan anggotanya pada lingkaran yang sempit. Dari sinilah muncul kesan “asyik sendiri” yang dikritik SCB.
Wajah Komunitas Sastra di Bali
Untuk menilai lebih jauh, mari kita tengok Bali. Penelitian yang dilakukan oleh akademisi Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, pada 2019—oleh I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani, Maria Matildis Banda, dan I Ketut Nama—memberikan potret konkret tentang komunitas sastra di Pulau Dewata. Sejak awal 2000-an, komunitas sastra di Bali tumbuh dengan pesat. Tak lagi terbatas di Denpasar, melainkan merambah kabupaten-kabupaten.
Di Buleleng ada Komunitas Mahima, yang dikenal aktif menggelar diskusi buku, pemutaran film, musikalisasi puisi, dan pementasan drama. Di Jembrana ada Komunitas Kertas Budaya yang diprakarsai sastrawan Wayan Udiana (Nanoq da Kansas). Di Denpasar, Jatijagat Kehidupan Puisi (JKP) kerap menjadi pusat kegiatan, merangkul berbagai kelompok teater dan sastra dari sekolah-sekolah.
Selain itu, banyak komunitas berbasis sekolah, Teater Solagracia di SMA 1 Negara, Teater Tanpa Nama di SMA 2 Negara, Teater Galang Kangin di SMAN 2 Amlapura, Teater Jineng di Tabanan, hingga Komunitas Lentera di Klungkung. Sebagian besar anggota komunitas ini adalah remaja SMA/SMK berusia 14–17 tahun. Menariknya, mayoritas anggota adalah perempuan (57,4 persen). Mereka tidak hanya menjadi objek karya, tetapi juga subjek, penulis, pemain teater, pembaca puisi, sekaligus penonton.
Kegiatan mereka rutin, 63 persen komunitas mengadakan aktivitas seminggu sekali. Bentuk kegiatannya beragam—diskusi, baca puisi, musikalisasi, hingga pementasan drama. Teater menjadi kegiatan paling diminati (48,1 persen). Banyak anggota bergabung karena ingin mencari inspirasi (48,1 persen), pengalaman baru, atau sekadar memperluas pergaulan.
Data penelitian ini menantang asumsi SCB. Benar bahwa ada komunitas yang tampak eksklusif, sibuk dengan lingkarannya sendiri. Tetapi di Bali, komunitas justru berfungsi sebagai ruang pembelajaran kreatif yang terbuka. Mereka melibatkan siswa, guru, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Kekhasan komunitas terletak pada karya cipta, bukan sekadar gaya hidup intelektual.
Komunitas Mahima, misalnya, telah melahirkan sejumlah penulis muda seperti Wayan Sumahardika, Wulan Dewi Saraswati, Juli Sastrawan, hingga Desi Nurani. Komunitas Kertas Budaya menumbuhkan nama-nama baru, termasuk Angga Wijaya, Ibed Surgana Yuga, dan Putu Agus Phebi Rosadi. Mereka bukan sekadar menulis untuk dinikmati internal, tetapi juga menembus media nasional dan forum lebih luas.
Fakta ini menunjukkan bahwa komunitas tidak selalu “asyik sendiri”. Justru sebaliknya, mereka menjadi pintu masuk bagi generasi baru untuk mengenal sastra dan menghidupi kreativitas.
Meski demikian, kritik SCB soal kritik sastra tetap relevan. Penelitian Udayana juga menyebut bahwa banyak penulis berbakat di Bali tenggelam karena tidak ada diskusi khusus atau dukungan lingkungan. Di sini letak persoalan, komunitas bisa sangat aktif, tetapi jika kritik obyektif kurang, karya-karya bisa terjebak pada euforia internal. Kritik akademik, jurnal, atau media independen masih dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan membuka perspektif baru. Dengan kata lain, komunitas memerlukan cermin dari luar agar tidak jatuh pada narsisme kolektif.
Antara Rumah dan Jerat
Komunitas selalu ambivalen, ia bisa menjadi rumah yang hangat, tetapi juga jerat yang membatasi. Ia bisa memunculkan solidaritas, tetapi juga homogenisasi selera. Ia bisa memperkaya karya, tetapi juga menekan kreativitas yang berbeda.
SCB mengingatkan kita agar tidak terlena pada romantika komunitas. Esainya “Sastra Komunitas” adalah seruan agar kita tetap kritis, jangan sampai sastra hanya menjadi pesta kecil di ruang sempit. Tetapi, temuan penelitian di Bali menunjukkan ada jalan lain. Komunitas bisa berkembang menjadi ruang belajar yang dinamis, ruang pertemuan lintas usia, dan ruang inspirasi yang melampaui batas internal.
Apakah benar komunitas sastra “asyik sendiri”? Jawabannya tidak bisa hitam putih. Ada komunitas yang memang terjebak dalam lingkaran eksklusif, hanya memuji dirinya sendiri. Tetapi ada pula yang berhasil membuka diri, melahirkan sastrawan baru, dan menyapa publik lebih luas.
Pengalaman Bali memperlihatkan bahwa komunitas bisa menjadi motor penting bagi pertumbuhan sastra. Mereka menghidupi kegiatan kreatif di tingkat lokal, memberi ruang bagi anak muda, dan menjaga agar sastra tetap hidup meski perhatian pemerintah minim. Festival Bali Jani yang digagas pemerintah provinsi sejak 2019, misalnya, juga berupaya merangkul komunitas sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan.
Pandangan SCB tetap relevan sebagai kritik, tetapi penelitian Udayana membuktikan bahwa komunitas tidak selalu asyik sendiri. Mereka juga bisa menjadi jembatan antara karya sastra dan masyarakat, antara ruang kecil dan ruang publik.
Mungkin, pada akhirnya, yang penting bukan sekadar apakah komunitas “asyik sendiri” atau tidak, melainkan bagaimana komunitas mampu menjaga keseimbangan merawat internalnya sekaligus menyapa dunia luar. Jika keseimbangan ini terjaga, maka komunitas sastra tidak hanya menjadi lingkaran kecil yang menutup diri, tetapi taman luas tempat sastra tumbuh, berbunga, dan dinikmati siapa saja. (*)
*) Penyair, esais, dan jurnalis lepas di Denpasar-Bali. Sejak 2018 telah menulis 15 buku, selain aktif sebagai penulis lepas dan kolumnis.

Angga Wijaya, (foto oleh Bonk Ava)