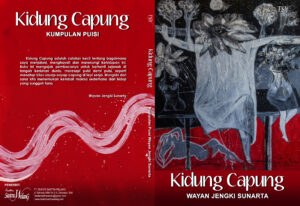DENPASAR, Teatersastrawelang.com – Di tengah dinamika dunia seni dan sastra Indonesia, nama Hartanto mencuat sebagai sosok yang konsisten menenun kata, menghidupkan ruang seni, sekaligus merawat nilai-nilai kemanusiaan. Lahir di Surakarta pada 1958, ia kini bermukim di Denpasar, Bali. Meski menempuh pendidikan formal di Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, arah hidupnya justru berpijak pada jalur sastra, seni rupa, dan jurnalisme.
Sejak masa remaja, Hartanto sudah menunjukkan minat mendalam pada puisi. Ia menulis sejak SMP, dan dari situlah benih kepenyairannya tumbuh subur. Karyanya kemudian menembus berbagai media arus utama: Bali Post, Tempo, Suara Pembaharuan, Femina, Hai, hingga jurnal kebudayaan CAK. Tidak berhenti di tingkat nasional, beberapa puisinya diterjemahkan oleh penyair Amerika, Thomas Hunter, dan dimuat dalam sejumlah publikasi di Prancis.
“Puisi bagi saya bukan sekadar kata indah. Ia adalah ruang perenungan, medium dialog dengan diri sendiri dan dengan semesta,” ujar Hartanto dalam sebuah forum sastra di Denpasar.
Dari Antologi ke Antologi: Jejak Karya yang Konsisten
Hartanto telah menorehkan perjalanan panjang dalam dunia puisi. Antologi pertamanya, Ladrang (Wianta Foundation, 1995), menjadi penanda serius langkahnya di ranah kepenyairan. Kemudian lahir karya-karya lain dalam bentuk antologi bersama: Dendang Denpasar, Nyiur Sanur (2012), Ibunda Tercinta (2021), Blengbong (2021), serta LIKE (2024).
Di tahun 2025, ia mencapai tonggak penting dengan menerbitkan antologi tunggal berjudul Ketawang (Balimangsi). Buku ini merekam perjalanan panjang kreatifnya, dari keresahan batin, refleksi sosial, hingga kedekatannya dengan alam Bali.
Selain puisi, Hartanto juga produktif menulis buku-buku seni rupa dan biografi. Bersama Putu Wirata, ia menulis Arie Smit Memburu Cahaya Bali (2000), sebuah buku yang mengupas perjalanan maestro pelukis Belanda yang lama tinggal di Bali. Ia juga menulis Image of Woman (2000) bersama DR. Wayan Sujana “Suklu”, serta Tree of Life (2018) tentang perjalanan seni pelukis Made Gunawan.
Perannya sebagai penulis pengantar buku tidak kalah penting. Hartanto dipercaya banyak seniman dan akademisi untuk menuliskan kata pembuka yang tidak hanya menjelaskan isi buku, tetapi juga memberikan perspektif kritis. Beberapa di antaranya adalah Peladang Kata (2019), Upacara Terakhir karya GM Sukawidana (2019), Autobiografi Kejahatan karya dr. Sthiraprana Duarsa (2019), hingga Sang Inisiator (2024).

Penggerak Seni Budaya
Bagi Hartanto, menulis adalah satu hal, tetapi menggerakkan seni budaya adalah hal lain yang tak kalah penting. Sejak 1983, ia sudah terlibat dalam kegiatan seni, menjadi ketua panitia lomba baca puisi se-Bali memperebutkan Piala Gubernur Ida Bagus Mantra.
Pada 1992, ia bersama perupa Made Wianta, Romo YB Mangunwijaya, dan maestro tari Sardono W. Kusumo menggelar acara Art for Flores, sebuah aksi solidaritas bagi korban gempa bumi Flores.
Lalu, pada 1996, ia mendirikan Balimangsi Foundation, lembaga seni budaya yang menjadi wadah penting bagi penerbitan buku-buku kebudayaan, diskusi, dan pameran seni rupa. Balimangsi kerap bekerja sama dengan museum, ruang seni, hingga media seperti Kompas Denpasar.
Selama lebih dari dua dekade, Hartanto melalui Balimangsi mengorganisir pameran seni rupa di berbagai kota, termasuk membawa seniman Bali tampil di panggung internasional seperti Beijing International Art Biennale (2008, 2010, 2012) dan Olympic Fine Art Beijing 2008.
Tak hanya itu, saat gempa besar melanda Yogyakarta tahun 2006, Hartanto turut menggagas Jogya Human Mission, kolaborasi seniman yang menghadirkan karya instalasi untuk membantu penyediaan air bersih di desa-desa terdampak. Aksi tersebut melibatkan seniman seperti I Wayan Sujana ‘Suklu’, Grace Tjondro Nimpuno, hingga sastrawan Putu Fajar Arcana.
“Bagi saya, seni bukan hanya soal estetika, tapi juga etika dan empati. Ia harus bisa menjawab kegelisahan zaman dan kebutuhan manusia,” kata Hartanto suatu kali.’

Bersama WS Rendra dalam sebuah acara seni budaya di Bali
Dari Kurator hingga Petani
Selain menulis dan menggerakkan komunitas, Hartanto juga pernah menjadi kurator ilustrasi cerpen Kompas (1999–2005) mendampingi Bre Redana. Perannya sebagai kurator memperlihatkan kemampuannya membaca bahasa visual, sekaligus menghubungkannya dengan narasi sastra.
Namun, di balik segala kesibukan itu, Hartanto memilih jalan hidup sederhana. Belakangan, ia menyebut dirinya “petani” di Bali Utara. Julukan itu bukan hanya metafora, tetapi juga cerminan pilihannya untuk kembali ke akar, mengolah tanah, sembari terus menulis.
Penghargaan dan Apresiasi
Atas kiprahnya, Hartanto diganjar berbagai penghargaan bergengsi. Pada 2008, ia menerima Obor Olimpiade Beijingdalam partisipasinya di Olympic Fine Art. Tahun 2023, ISI Denpasar menganugerahinya Bali Dwipantara Natha Kerthi Nugraha sebagai penyair sekaligus maecenas seni rupa. Setahun kemudian, ia menerima Bali Jani Nugraha dari Gubernur Bali.
Penghargaan-penghargaan ini mempertegas posisi Hartanto sebagai figur penting dalam lanskap seni dan sastra Indonesia, khususnya Bali.
Menjembatani Sastra, Seni, dan Kehidupan
Hartanto adalah jembatan yang mempertautkan sastra, seni rupa, dan kehidupan sosial. Puisinya lahir dari perenungan, namun aktivitas organisasinya menunjukkan bahwa ia juga seorang man of action. Ia percaya bahwa karya seni dan sastra harus punya daya hidup, menyentuh banyak orang, dan membuka ruang dialog lintas generasi.
Kini, di usianya yang matang, Hartanto tetap menulis, tetap hadir dalam pameran dan diskusi, sekaligus tetap setia pada tanah tempat ia berpijak. Sosoknya menjadi inspirasi, bahwa kesetiaan pada kata dan seni bisa berjalan seiring dengan kepedulian pada kehidupan nyata. (tsw01)